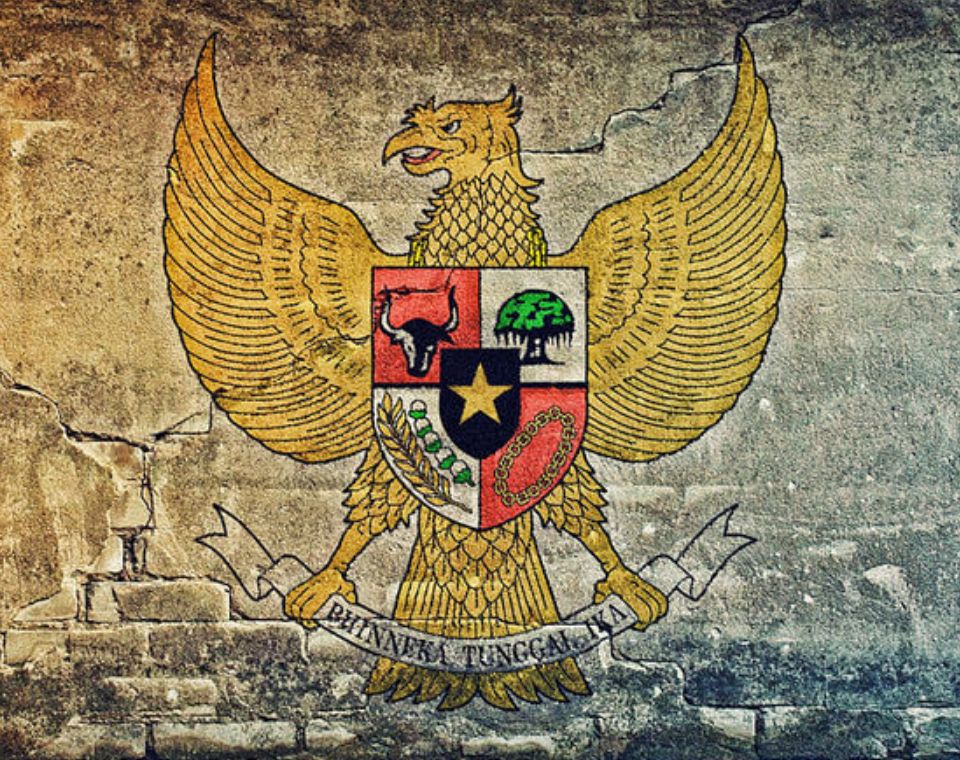Realitas tersaji di dalam konfigurasi politik nasional kita syarat dengan konflik kepentingan dan rentan perpecahan baik itu entitas politik dan sosial. Hal ini tentu mengundang keprihatinan yang sangat mendalam. Pokok persoalan dan gejolak kerap muncul sebab ego individualisme dan ideologi kepentingan kelompok yang mana lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa. Padahal sebuah cita-cita luhur telah diamanahkan untuk digerakkan oleh keinginan yang sama sebagaimana harapan para pendiri bangsa, yaitu pembangunan menyeluruh yang peletakan pondasinya berdasarkan pada Ideologi Negara yaitu Pancasila.
Saat ini perhatian dan penekanannya adalah bagaimana masyarakat dalam konteks ini seluruh Warga Negara Indonesia dengan beragam kelompok politik, sosial, budaya, agama dan sebagainya, dapat merenungkan kembali hakekat dan eksistensi Pancasila seutuhnya. Kehendak yang bermuara pada terciptanya masyarakat yang satu, yaitu masyarakat pancasillais. Artinya bagaimana masyarakat dengan beragam entitas itu dapat bergaul dan hidup tanpa friksi serta gejolak dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
Keinginan tersebut, sejatinya sama dengan apa yang selama ini menjadi gagasan dan pemikiran seorang rohaniawan sekaligus pemikir sosial, John Djikstra, SJ., dan Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ., seperti yang tertuang di dalam buku Biro Sosial. Di dalam buku tersebut, mereka mewacanakan pengamalan Pancasila dengan ragam turunannya, seperti Buruh Pancasila, Petani Pancasila, Nelayan Pancasila, Dokter Pancasila, Politisi Pancasila, Ekonom Pancasila, dan lain sebagainya.
Pancasila yang terefleksikan dalam perilaku sehari-hari adalah amalan nyata sehingga dapat menjelma sebagai masyarakat yang pancasilais. Hal ini adalah manifestasi sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia.
Sayangnya, pola dan polah masyarakat kita saat ini telah dikonstruksi oleh beberapa nilai yang destruktif, diantaranya individualisme, materialisme, dan kebebasan kebablasan. Dalam kehidupan sosial politik, nilai-nilai tersebut tereduksi dalam keseharian. Gambaran individualisme muncul misal dari tindakan elite kekuasaan politik, ekonomi dan lainnya, yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya.
Spirit ke-Aku-an yang menajamkan rasa primordialime dan sentimen kepada yang lain, dikarenakan orientasinya hanya terfokus pada individu maupun kelompok. Ke-Aku-an yang semakin menisbikan nilai-nilai etika, norma, budaya, bahkan agama yang sejatinya telah terepresentasikan dalam sila-sila Pancasila.
Ego sektoral sepertinya juga merambah di dalam kehidupan masyarakat kita, yang merasa kuasa atas yang lain atau mayoritas mendominasi atas minoritas. Kekhawatiran tentu bila kemudian mengakibatkan munculnya konflik dan kekerasan sebagai jalan keluar, bukan dengan dialog atau musyawarah sebagai cara yang santun dan demokratis serta lebih mencermikan kita sebagai bangsa yang beradab.
Menguatnya manuver dalam kungkungan ego sektoral untuk menggapai kekuasaan dan keinginannya ini semakin tajam ketika sisi materialisme beriringan dengan ego individualisme. Hampir selalu kita dengar dan lihat sebuah ambisi kekuasaan selalu berkelindan dengan materi (uang). Ketika ingin menjadi anggota dewan atau kepala desa misalnya, mereka berani membarternya dengan uang. Atau korporasi yang “membeli” kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memuluskan jalannya pembangunan perusahaan tanpa melibatkan bahkan kadang merugikan masyarakat dan stakeholder lainnya.
Praktek paham materialisme yang mengurita dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat mampu “membunuh” spirit ke-Aku-an ideologi bangsa kita. Kenapa tidak, karena pada akhirnya ideologi pasar lebih mendominasi dan semua digerakkan oleh hukum pasar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada akhirnya tergerus dan terancam hilang dalam ingatan maupun praktek keseharian.
Setali dengan itu era eformasi yang ditandai dengan semakin terbuka dan dinamisnya kebebasan dalam berdemokrasi, seakan menjadi ruang ekspresi dengan kebebasan penuh. Pemahaman dan pemaknaan seperti ini tentu membawa dampak yang tidak baik dalam tata kelola dan perilaku bermasyarakat dan berbangsa.
Kebebasan penuh seolah-olah menjadi pintu masuk untuk bermain bebas demi kemenangan politik dan sosialnya. Padahal jelas bahwa kebebasan dimana dan apapun wujudnya tentu dibatasi oleh norma dan aturan sebagaimana Pancasila yang telah lama disepakati menjadi dasar Negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam mengatur arah pambangunan bangsa.
Budayawan KH. Musthofa Bisri pernah menekankan tiga hal pemikirannya. Pertama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan Indonesia, sesungguhnya kita telah mempunyai semboyan agung yang bahkan sejak di sekolah dasar telah diterang-uraikan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan karena Tuhan menciptakan demikian adanya sebagai anugerah. Menerima perbedaan: etnis, bahasa, budaya, agama dan perbedaan lainnya, memerlukan kearifan besar karena menerima perbedaan itu jauh lebih sulit daripada melakukan pekerjaan.
Langkah menerima perbedaan tidak berkaitan dengan kompetensi, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap. Perbedaan semestinya menjadi energi dan perekat pemersatu paling fundamental dalam pembangunan bukan sebagai momok yang ditakuti. Bukan dijadikan bahan baku utama untuk meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara: menebarkan kebencian, konflik dan kekerasan. Dengan memaknai semboyan tersebut secara jernih dan mengamalkannya dengan arif, sejatinya kita telah merefleksikan kandungan nilai-nilai Pancasila.
Kearifan Lokal
Kedua adalah bangsa ini sesungguhnya kaya dengan budaya yang otomatis terkandung karena keanekaragaman itu. Budaya lokal yang terpendam di tiap daerah lalu terpancar sebagai kearifan lokal. Tugas bagi setiap anak bangsa adalah terus dengan sekuat tenaga menggali budaya dan kearifan-kearifan lokal lainnya sehingga semakin memberi sumbangsih bagi pencapaian Indonesia satu yang berkarakter Pancasila.
Kolaborasi kebudayaan dan kearifan lokal yang padu, terbina dan terpelihara tentu akan memberi panduan ditengah penetrasi dan arus budaya global yang kuat sekarang ini. Norma dan etika tentu menjadi bagian tak terpisahkan dalam prosesnya karena kita hidup di tengah masyarakat dan bangsa. Norma dan etika yang menjadi pijakan dalam pengembangan budaya dan kearifan lokal akan memberikan tuntunan kebaikan dan kebenaran.
Ketiga, untuk menjadi Negara berharkat dan bermartabat baik, tentu yang harus diciptakan terlebih dahulu adalah pengusahaan pribadi-pribadi anak bangsa yang mempunyai citra Pancasilais. Pencitraan positif yang berasaskan nilai-nilai kultural, sosial dan transendental agama secara konsisten. Apa yang dilakukan dan digalakkan kembali oleh pemerintah secara serius dengan membumikan empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan GBHN adalah salah satu usaha untuk itu.
Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembumian tersebut, tentu harus diimbangi dengan tingkat konsistensi yang tinggi dalam pembelajaran dan pendidikannya dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas serta tidak diragukan lagi pengamalan Pancasilanya secara utuh, baik dan benar. Mengapa? Karena pembelajaran dan upaya-upaya yang tidak konsisten, sporadis dan tidak benar akan menghasilkan output yang tidak maksimal bahkan dikhawatirkan salah dalam menafsirkan kandungan dalam nilai-nilai pancasila.
Lantas apakah dengan dilaksanakannya ketiga hal tersebut akan mampu membentuk kehidupan masyarakat yang pancasilais sebagaimana yang dicitakan? Memang tidak ada jaminan 100 persen dalam penciptaan apalagi implementasinya. Namun, dalam tataran yang paling rendah, ketiga faktor tersebut adalah anak tangga awal atau pijakan pertama untuk membangun dan memupuk semangat Pancasila dalam keseharian kita.
Kesadaran akan ketiga nilai tersebut, jika tidak tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam di individu-individu, yang terjadi adalah suasana bathin yang sulit untuk mengkreasikan jembatan pergaulan antar individu, masyarakat dan negara. Jadi kiranya, kesadaran terhadap eksistensial Pancasila-lah yang menuntun dalam upaya pembentukan masyarakat yang Pancasilais .
(Saifuddin Hafiz)
Seniman/Pemerhati Sosial Budaya